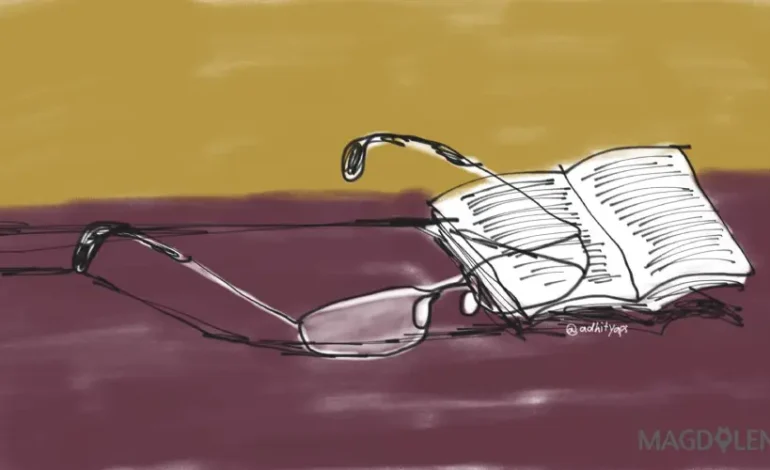Botak Pecak
Botak menandakan duka cita bagi perempuan Asmat jika ada sanak keluarga yang meninggal. Pecak dalam bahasa Asmat berarti "malang".

Agats, Januari – Februari 2018
Air pasang untuk ke sekian kali mendorong harapan dan suara minta tolong, yang mengambang di atasnya yang masih cokelat, keruh, dan jorok. Segalanya terbawa bersama serakan botol air mineral dan sampah rumah tangga, bahkan sampah sumpah serapah yang dibuang sembarangan ketika meludah air pinang dengan bebasnya ke daratan perut ibu, tanpa mereka indahkan perasaan lumpur yang dipijaki. Tak ambil pusing dan semua menganggapnya lumrah. Walau mungkin meninggalkan kesan jorok dan jijik bagi sebagian yang bukan penikmat kudapan pinang kering dengan sedikit kapur yang melengkapi rasa dan memberikan sensasi kesempurnaan.
Daratan lumpur seperti dilukisi dengan karya abstrak dari mulut-mulut pencinta pinang yang kerap ngomong ngalor-ngidul seraya memamerkan tumpukan gigi yang merah agak mengarah kehitaman. Kadang juga berteriak dengan lantang ”bareoooo….pecak (ooo..betapa malangnya)”. Makin lama perutnya kian membuncit dan lipatannya melampaui gundukan tai sinak.
Aku hidup di atas kota rawa yang terlihat berjerawat dan agak bopeng karena hamparan gundukan kotoran hewan berwarna merah, sepintas terlihat seperti monster udang berukuran tanggung yang kerap keluar rumahnya waktu air pasang sempurna. Sinak. Begitulah penduduk setempat menamainya. Namun perut Asmat bertambah besar sekarang. Bukan karena ibu sedang mengandung, namun karena lapar perutnya sampai menggembung sampai membusung. Bau lumpur semakin busuk. Bercampur dengan kepedihan dan derita yang semakin menggelembung. Seperti anak lapar tertunduk lunglai karena tidak dapat makan sagu, itulah wajah Asmat yang kini aku tempati. Yang tersisa bukan lagi ukirannya yang mendunia namun perut buncit para anak dan ibu yang diisi dengan angin dan entah apa. Sesekali aku ingin mengutuk dan mendatangi satu per satu manusia yang kutemui dan bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini ?”.
Asmat menangis dalam kesedihan mendalam. Asmat enggan membalas tatap. Ia sibuk meratap. Asmat enggan membalas jawab. Padanya semua melempar tanya dan salah. Padanya semua menagih pertanggungjawaban.
Aku melihat perempuan botak meraung menengadah. Memohon seumpama ada di atas kepalanya yang bisa berbelas kasih. Bersamanya pula aku merenungi wahai apa ini. Dalam kesedihan yang mendalam, hatiku membuncit terisi angin kesedihan. Botak kepalanya baru cukur. Sebuah pertanda duka cita. Bayi kecilnya yang belum dua tahun baru saja diselimuti kain putih hingga menutup wajahnya. Ia mati. Ada yang membunuhnya. Sebuah monster besar tapi ia tidak terlihat. Terlalu halus dan tipis seperti selaput. Tapi ia besar dan mengerikan. Ia datang tanpa pemberitahuan. Ia datang tanpa keliru alamat. Ia membawa sekantung penuh entah apa. Hendak ia bagikan rata pada anak-anak. Seperti sinterklas mata satu. Ia membunuh. Tapi ia entah apa.
Adonimia Yeripit tidak pernah menyangka ia antar anaknya menuju sebuah yang semua orang sebut sebagai kematian. Biasanya ia pergi ke seputaran rumah sakit untuk bermain di Tugu Tangan atau mengantar anaknya yang lain bermain bola kaki dari gulungan kertas bekas pemberian fotokopi di lapangan Koramil.
Sekarang ia harus botak. Sekarang ia memilih membotaki kepalanya. Ia kehilangan anak bungsunya. Yang kaki dan tangannya mungil tipis tulang. Dan perutnya menggembung buncit. Keras dan seperti nyaris meledak.
Sekarang ia harus botak. Dan menangisi lebih banyak hal lagi. Soal bagaimana ia pergi gereja dan mencari di mana derma esok hari. Soal kesedihannya melihat bayi kecilnya yang masih ringkih dan harus melihatnya dikubur dalam rendaman lumpur yang menggenang. Soal bagaimana mengantar bayi kecilnya yang kaku dan tidak bergerak.
Ia hanya kembali meraung sambil menengadah. Berharap ada belas kasihan dari atas kepalanya atas kemalangannya.
Adonimia berduka dan malang. Asmat berduka tapi tidak malang.
Aku jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada Asmat tahun lalu. Waktu hujan mengguyurnya, maka ditampakkanlah keindahan luar biasa.
Namun kini hujan seumpama ia air mata. Ia menangis.
Atau mungkin cinta ini yang absurd. Aku terpikat pada lumpur. Pada ketenggelaman lumpur. Tapi rasanya aku kehilangan arah untuk berjalan di dalamnya. Kompas batinku mati seketika saat melihat semua kejanggalan yang terjadi. Betapa teririsnya bersentuhan dengan anak-anak yang kekurangan gizi untuk tubuh maupun otak mereka. Namun yang membuat mereka kuat adalah ibu.
Adonimia dan aku tidak banyak memiliki kisah. Tapi setiap pertemuan dengannya selalu ada keceriaan dan keramahan yang tidak pernah habis dia kembangkan. Membuatku merasa berat untuk berpisah dengannya. Ibu yang ramah juga baik dan cantik. Meski selusin giginya merah kena noda pinang, meski ibu jarang mandi namun selalu memberikanku camilan pinang kering lengkap dengan sirih buah dan sedikit kapur dalam lintingan plastik bening. Ibu yang menyapaku lembut dengan nama anakku sayang meski sebenarnya aku lebih tua darinya beberapa tahun. Selalu menertawakanku saat aku mabuk pinang.
Aku membawakannya rokok kretek dan ia memberiku seumpama cinta dalam lempengan pinang kering yang pipih. Hampir seukuran dengan hosti yang aku makan pada perayaan Ekaristi hari Minggu. Hanya saja diameternya kurang mencukupi. Kami duduk di pasar bak preman pasar yang nimbrung di dekat bait suci. Berbicara panjang lebar tentang banyak hal dengan diselingi tawa muncrat bersama semburan tai pinang dari mulut masing-masing.
Anak-anaknya sebanding dengan ikan gelodok yang berseliweran dekat papan sambil sesekali berselancar dengan tubuhnya dan menciptakan nada “clup…clup…clup” di atas kulit air. Kami menyaksikan pengemudi motor yang tanpa helm, tanpa tahu aturan lalu lintas, tanpa lampu merah. Bahkan tanpa takut untuk ditilang polisi karena memang di kota ini tak ada satu orang pun yang memiliki SIM.
Kami hidup bersama alam dan kebebasan. Bersama lumpur dan karaka (kepiting) pun gelodok yang berpesta pora dalam kubangan lumpur.
Rasa nyaman begitu besar ketika aku masih dipanggil “sayang” oleh mereka. Tak takut aku berenang dalam lumpur cokelat penuh tai. Karena banyak ibu dan ayah serta saudara yang mencintaiku bahkan berani menamaiku dengan panggilan sayang. Namun kini aku sangsi. Saat aku melintas di depan pasar, tak ada lagi ibu yang melambai dan memberiku camilan pinang. Semuanya seakan berpaling. Semuanya sibuk membotaki kepala sambil meraung dan meratap.
Pada papan reot atau hujan tengah malam. Aku dilema. Seakan rasa benci pecah ketika melihat sinterklas bermata satu. Berpapasan denganku. Campak dan gizi buruk dalam batinku bahkan lebih sadis dari ulat sagu yang menggerogoti pangkal sagu sendiri. Ibu dan anaknya sama-sama menderita gizi buruk dan campak kini dan aku merasa seperti gelodok tak berguna. “Ya Tuhan….aku ini gelodok tak berguna”. Gumamku disela rintik malam yang ke sekian kalinya setelah disembunyikan awan untuk beberapa saat yang lama.
Namaku Adonimia Yeripit. Anakku mati. Meninggal. Wafat. Sa pu anak ada hilang ditelan mati.
Dia anak ketujuhku di usia 23 tahun. Namanya Aloysius Desnam. Kuberi nama dia Aloysius, nama pemberian seorang Frater asal Bandung. Ia memberi nama anakku seperti nama sekolahnya dulu.
Aloysius anakku paling kecil. Paling mungil dan paling tipis. Sejak ia lahir ia tidak punya pipi bulat dan mata bersinar dengan bulu mata lentik seperti keenam kakaknya.
Matanya bulat nyaris keluar seperti mantan mantri gila perempuan di kampung kami dulu. Aku sempat berpikir jangan-jangan anakku terkena kutukan memiliki wajah dengan mata sepertinya.
Kulitnya terbungkus kulit tanpa daging. Bahkan aku bisa melihat dan meraba sendi-sendi tulangnya.
Perutnya membusung seperti nyaris meledak. Ketika aku sekolah dulu, aku pernah diberi lihat guruku sebuah gambar. Sebuah negeri bernama Ethipoia atau Ethiapoi atau Etaaipoi, entah apa namanya. Ada sebuah gambar seperti anakku. Anak dengan perut membusung nyaris meledak tapi mata belo nyaris keluar yang cahayanya redup tatapannya kosong. Gambar itu seperti anakku.
Aku adalah perempuan celaka yang seluruh hidup sisanya kuhabiskan untuk menyesal. Aku menyesal tidak bertahan sebentar lagi saja untuk tetap sekolah. Aku merasa celaka. Dan berhutang pada diriku sendiri di masa depan. Aku berutang pada anak-anakku. Yang mati kelaparan. Yang mati dengan tulang tipis dan perut nyaris meledak. Aku berutang pada mereka.
Kalau aku sedikit saja bersabar dengan mulut dan pukulan busuk orang tuaku, aku akan memakai kebaya kutubaru atau kebaya Kartini dengan kain di kabin pesawat maskapai kelas satu. Dan kalau aku sedikit saja bersabar untuk tidak menukar usia remajaku dengan pinangan yang tidak seberapa berarti — aku bisa mengajak dan melayani anakku sendiri di dalam pesawat agar tidak kelaparan. Dan anak itu bisa Aloysius bisa bukan. Bisa ia gemuk menggemaskan, bisa juga tetap tipis tulang ringkih patah.
Atau bisa juga aku menjadi pemain peran di gedung teater atau menjadi penyanyi di Broadway.
Guruku pernah mengatakan aku adalah anak Asmat paling cerdas. Aku fasih berbahasa Inggris dua kali lebih cepat dibanding temanku dari Toraja atau Manado. Aku paling gigih mencari tugas mewawancarai sejarah atau meneliti pergerakan tanaman terhadap matahari. Aku mengikuti lomba sprint dan maraton yang persyaratannya adalah laki-laki. Aku mampu menganalisa persamaan-persamaan yang bahkan tidak mampu dikerjakan guru Sejarah atau Bahasa Inggrisku. Aku kepala goyang dan badanku paling lentur di antara semua kawan. Aku pandai mengukir dan menganyam noken. Aku adalah anak paling cerdas yang pernah ditemui guruku di Asmat.
Sampai semuanya berhenti.
Pinangan tidak seberapa berarti itu mengantarku pada sebuah awal yang sebenarnya bagian paling akhir.
Pernikahan yang melelahkan. Pukulan dan makian. Mengandung ketujuh anak. Badan dan vaginaku lelah. Aku hanya terus disetubuhi tanpa diberi makan dan uang belanja. Aku mencari sendiri kayu bakar untuk memanaskan sagu yang kuperoleh susah. Laki-laki di rumah kami hanya berfungsi menyetubuhi dan menghamili. Akulah kepala keluarga sekaligus ibu. Aku harus membelah kayu bakar dan memetik pucuk pakis di lumpur halaman sekolah inpres sambil menggendong dua anakku yang masih bayi. Sementara kelima anakku mulai merengek kelaparan.
Tidak ada yang bisa kumasak. Tidak ada yang bisa kupakai membeli apa yang bisa kumasak. Tidak ada yang bisa kucari selain pucuk pakis atau kangkung jorok. Sungai terlalu jauh. Tidak dapat kuserok ikan atau udang seperti yang digambarkan dalam iklan wisata alam. Urusanku terlalu banyak dan brengsek untuk pergi berjalan jauh ke sungai dan hutan. Anak balita yang terlalu banyak dan penuntut.
Kalau sudah begitu dengan kesal kuberikan mie instan supaya mereka kunyah mentah-mentah. Hingga mereka kenyang dan mulai diam. Urusanku terlalu banyak untuk memenuhi standar yang bahkan tidak pernah cocok untuk kami. Kesehatan apalah itu. Biar sudah!
Urusanku terlalu banyak. Mengangkang melayani libido laki-laki. Mengurusi balita yang selalu merengek. Mencari kayu bakar untuk menjarang air guna putar kopi. Urusanku terlalu banyak. Memberi makan banyak sekali orang. Aku hanya mampu turun lumpur dan memetik pakis. Badanku sendiri tidak ada isi dan tenaga. Aku kelaparan. Aku menyesal.
Seandainya aku bertahan sedikit saja. Aku yakin bisa menjadi perempuan pertama yang menjadi bupati. Atau perempuan pertama dari kampungku yang menjadi pramugari atau pilot. Atau perempuan pertama yang menjadi apa pun yang aku inginkan. Yang memastikan anak-anakku tumbuh cerdas dan segar badannya. Yang memiliki otoritas atas tubuhku. Menentukan kapan tubuhku: untuk mengandung, untuk melahirkan, bahkan disetubuhi.
Aku ingin membayar utangku. Aku ingin memperbaiki. Aku ingin anakku kembali. Kutumbuhkan menjadi anak yang tidak nyaris meledak perutnya.
Aku ingin jika aku membotaki kepalaku, itu karena aku memiliki hak atas tubuhku dan menjadi gembira karenanya. Bukan karena botak dukacita. Bukan karena aku merayakan kematian anakku. Bukan. Tidak pernah sekalipun.
*Untuk Asmat sayang o. Cepat sembuh Asmat. Jangan sakit. Jangan sakit. Cepat sembuh.
Faustino Atbar dan Trias Yuliana Dewi adalah dua teman yang sekarang tinggal di Asmat. Mereka terlanjur jatuh cinta pada kedalaman lumpur Asmat. Tidak pernah selesai membicarakan keindahan Asmat yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata kepala.