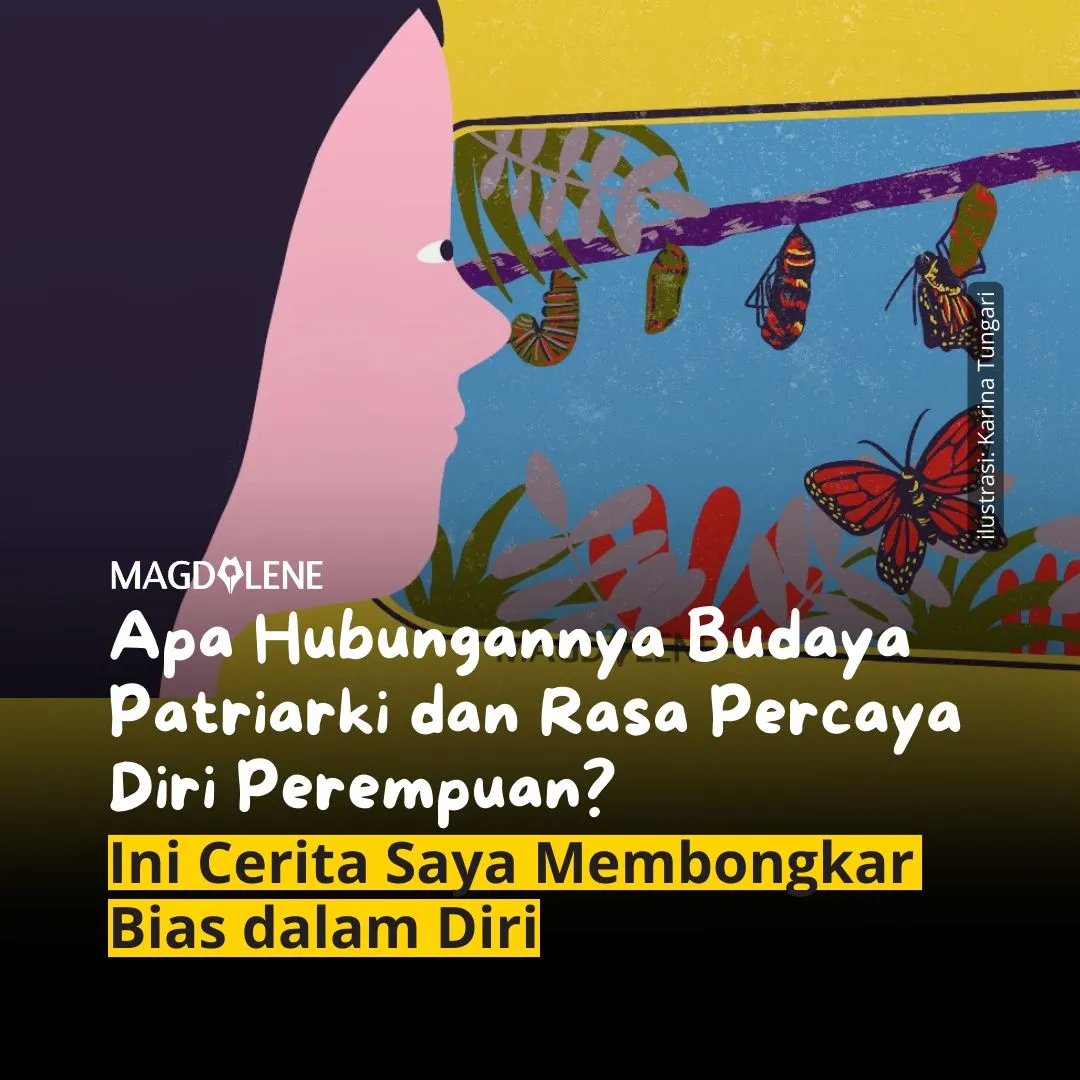Konferensi Anti-Feminisme: Propaganda Ahli Pelintir Data
Sebuah konferensi oleh Hizb ut Tahrir menjabarkan kegagalan feminisme dalam menjawab tantangan para perempuan di seluruh dunia.

Pada 4 April 2020, ada sejumlah tagar yang kontra dengan feminisme muncul di Twitter, seperti #GenderEqualityUnmasked, #BongkarKedokKesetaraanGender, #MuslimahTolakGenderEquality, dan #UninstallFeminisme.
Saat saya telusuri lebih lanjut, tagar-tagar tersebut ternyata untuk mengawal acara sebuah konferensi internasional daring bertajuk Beijing +25: Has The Mask Of Gender Equality Fallen?, sekaligus kampanye anti-kesetaraan gender yang diinisiasi oleh divisi perempuan dari kantor pusat media Hizb ut Tahrir.
Konferensi tersebut diadakan pada 4 April 2020, dimulai pada jam 15.00 WIB melalui siaran langsung di kanal YouTube ALWaqiyahTV. Ada tujuh perempuan yang menjadi pemateri dalam acara tersebut, yaitu Zeineb Djebbi dari Tunisia, Reem Allouche dari Australia, Zehra Malik dari Turki, Dia Najjareen dari Lebanon, Iffah Ainur Rochmah dari Indonesia, Zeina As’ad dari Palestina, dan Dr. Nazrreen Nawaz yang mewakili divisi perempuan dari kantor pusat media Hizb ut Tahrir, organisasi politik pan-Islamis yang terlarang di Indonesia itu.
Melalui siaran pers tertanggal 12 Maret 2020, organisasi itu mengklaim konferensi tersebut sebagai respons atas kegagalan setelah 25 tahun deklarasi Beijing Platform for Action (BPFA) atau yang disebut juga Beijing +25. BPFA adalah kesepakatan yang diinisiasi PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Disciminations Againts Women) pada tahun 1995 di Beijing.
Selama lebih jam lebih konferensi berlangsung, saya menangkap bahwa meski para pemateri membahas isu yang berbeda-beda, garis besar poin pembahasan mereka sama, yaitu menjabarkan kegagalan feminisme dalam menjawab tantangan para perempuan di seluruh dunia.
Hal tersebut mereka buktikan dari beragam ketimpangan yang masih dirasakan para perempuan di beberapa negara. Argumen dasar mereka sama, yaitu feminisme adalah hasil budaya Barat yang mengabaikan keragaman identitas dan budaya para perempuan.
Selain itu, para pemateri juga berargumen bahwa kesetaraan yang diidealkan oleh feminisme adalah ilusi yang akan membawa para perempuan semakin jauh dari akar identitas dan kodrat sebagai seorang ibu.
Dasar argumen tersebut, karena feminisme menggambarkan perempuan ideal adalah yang mandiri secara finansial, sukses berkarier, dan memiliki kebebasan atas tubuh. Perempuan yang demikian dianggap akan merusak stabilitas hubungan dalam keluarga dan masyarakat.
Akibatnya, feminisme juga dianggap menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Feminisme juga dianggap penyebab degradasi moral karena keras menerapkan batas usia pernikahan, tetapi permisif terhadap perbuatan yang dianggap menyimpang dari kodrat manusia.
Contoh penyimpangan yang dimaksud termasuk pernikahan sesama jenis, surogasi (ibu pengganti), hubungan seks sebelum menikah, dan aborsi. Berangkat dari deretan kegagalan feminisme tersebutlah, mereka menawarkan solusi lain yaitu penegakan hukum Islam di bawah bendera khilafah.
Baca juga: Ada Apa dengan (Kelompok Anti-) Feminisme
Ahli pelintir data
Pergerakan anti-kesetaraan gender ini sudah terlihat aneh sejak awal kampanye mereka di media sosial. Kelompok ini kerap menggunakan data-data permasalahan yang dihadapi perempuan dan kritik-kritik terhadap feminisme untuk menjustifikasi kampanye mereka.
Contohnya dapat dilihat pada utas yang ditulis oleh salah satu anggota Divisi Media Pusat Hizb ut Tahrir Kawasan Asia Tenggara, Fika Komara, dan diunggah di akun Twitter MuslimahNewsId (@m_newsid).
Utas tersebut dibuka dengan kutipan seruan dari para aktivis feminis dari 35 negara se-Asia Pasifik dalam Forum Masyarakat Sipil dan feminis Muda yang diadakan oleh badan PBB khusus untuk ekonomi sosial Asia Pasifik (UNESCAP) pada 22-26 November 2019 di Bangkok, Thaliand berikut ini.
“Kami marah. 25 tahun sejak Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, masih jauh dalam pencapaian kesetaraan gender. Ketimpangan kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya menjadi lebih besar dari sebelumnya.”
Komara menyebutkan, seruan di atas merupakan bentuk kemarahan para aktivis yang dipahami sebagai bukti bahwa kesetaraan gender adalah ilusi. Ia menyebutkan bahwa para feminis putus asa karena ternyata keterbukaan akses terhadap pekerjaan yang selama ini diperjuangkan justru berakibat eksploitasi bagi kaum perempuan itu sendiri.
Padahal seruan yang mewakili suara 300 aktivis yang hadir dalam forum tersebut untuk mengkritik pihak pemerintah yang tidak serius dalam menerapkan penanganan 12 bidang isu yang disoroti dalam deklarasi BPFA.
Berdasarkan kengawuran tersebut, saya coba mencari contoh lain dengan memilih secara acak unggahan di akun Instagram @kesetaraangenderunmasked. Saya coba memeriksa salah satu unggahan tanggal 17 Maret 2020.
Tertulis dalam unggahan tersebut, hasil penelitian lembaga riset pasar IPSOS tahun 2018 berupa data negara-negara di Eropa yang mendapat skor tinggi indeks kesetaraan gender, justru merupakan negara dengan tingkat pelecehan terhadap perempuan yang tinggi.
Pada unggahan tersebut, tercatat persentase pelecehan yang terjadi di Swedia adalah 81 persen, Denmark 80 persen, Perancis 75 persen, dan Inggris 68 persen. Jika ditelusuri, sumber data tersebut berasal dari salah satu artikel The Guardian yang ditulis untuk memaparkan fakta kesadaran publik akan kekerasan terhadap perempuan masih rendah, meski telah ada gerakan #MeToo.
Baca juga: Apakah Feminisme Bisa Selaras dengan Ajaran Islam?
Data persentase tersebut jelas tidak dapat digeneralisasi untuk menggambarkan realitas di seluruh dunia, karena IPSOS melakukan survei hanya di Eropa dan melibatkan 28.115 responden. Jadi tidak serta-merta diartikan kekerasan terhadap perempuan di Eropa lebih tinggi dari negara-negara lain di luar Eropa.
Tidak hanya dalam unggahan, pelintiran data juga saya temukan dalam paparan orasi saat konferensi. Iffah Ainur Rochmah dalam orasinya yang berjudul “Progress or Oppression from the Narative: Women’s Empowerment through Employment?”.
Rochmah menyajikan data dari artikel TheGuardian.com yang berjudul “The Rise of ‘Breadwinner Moms’ is Less a Win For Equality Than It Looks”. Melalui artikel tersebut ia ingin menunjukan bahwa alih-alih mendapat kemapanan ekonomi, para perempuan pekerja dan kepala keluarga justru mendapat kesulitan.
Jika hanya melihat dari judul artikel mungkin bisa percaya dengan penjelasan yang dipaparkan Rochmah. Namun jika dicek kembali isi artikel, ia jelas tidak memberitahu secara utuh inti dari artikel.
Pada tulisan utuh, artikel tersebut justru ditulis untuk mengkritik pemerintah Amerika Serikat yang tidak memiliki kebijakan yang “ramah” bagi perempuan, padahal 40 persen pencari nafkah utama adalah perempuan. Artikel tersebut justru menekankan bagaimana peran gender tradisional adalah penyebab kesulitan yang dihadapi para perempuan pekerja dan kepala keluarga.
Bahkan dalam artikel tersebut, penulis menyayangkan keterlambatan AS dalam mengenali manfaat feminisme. Selain itu, dalam artikel tersebut juga tertulis pergeseran peran gender dari yang konservatif menjadi lebih cari telah memberi banyak manfaat dari keluarga.
Konferensi itu hakikatnya adalah sebuah pertemuan untuk bertukar pendapat dan bermusyawarah agar mampu memecahkan suatu masalah. Oleh sebab itu jika mengklaim sebagai acara #Konferesi perempuan, sudah sepatutnya ada keterlibatan para perempuan dari beragam kalangan dan identitas.
Nah, jika solusi yang ditawarkan cuma satu, bersifat mutlak, dan tidak melibatkan pandangan yang beragam, bahkan data yang digunakan pun dipelintir, silakan disimpulkan sendiri apakah acara tersebut sebuah konferensi atau propaganda belaka.