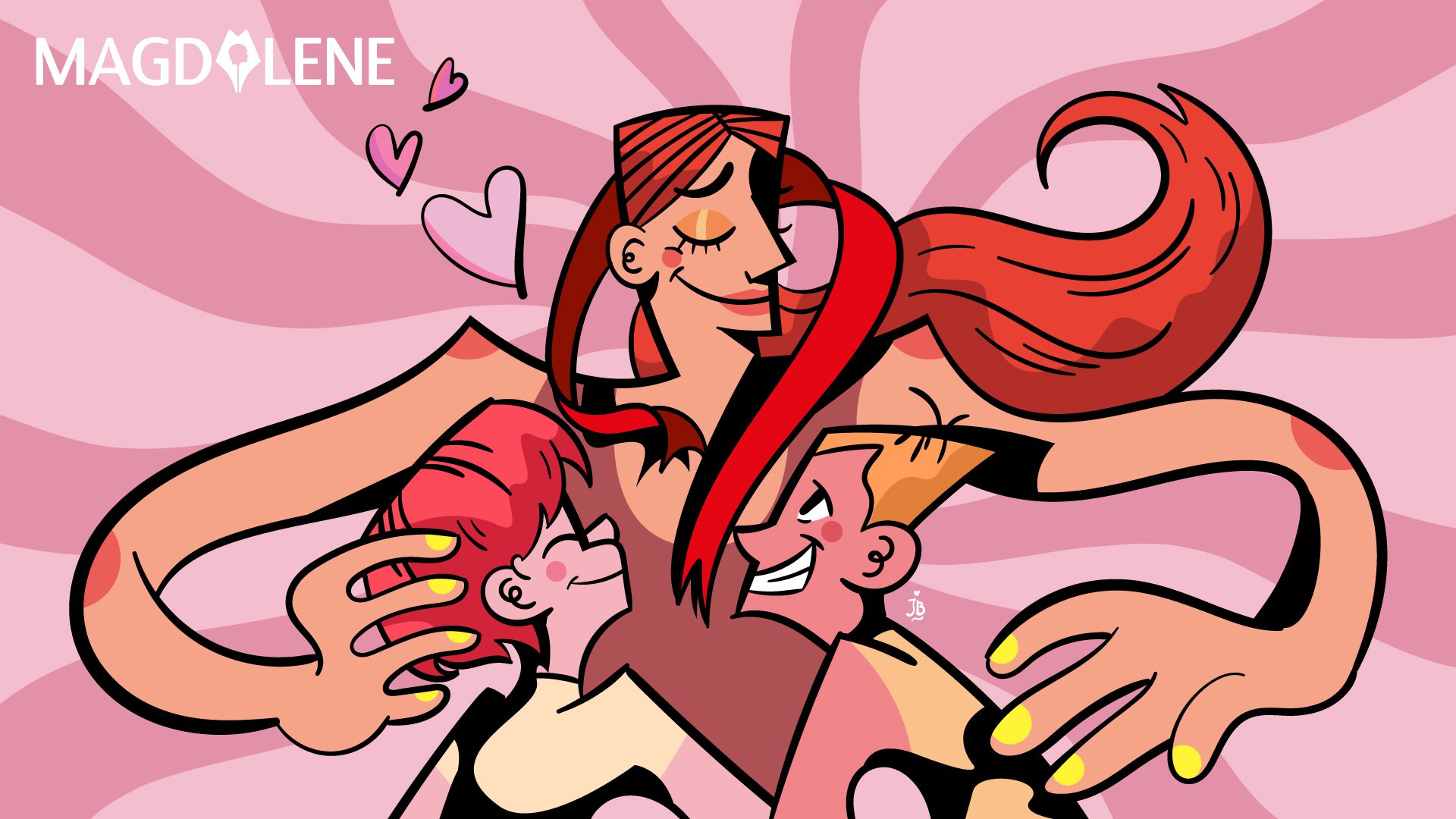Perempuan Bukan Barang Dagangan, Tak Punya Masa Kadaluwarsa
Berhentilah menyebut perempuan dengan istilah perawan tua atau tidak laku.

Perempuan di Indonesia masih “terpagari” berbagai hal dalam kaitan dengan pernikahan. Pagar yang dimaksud adalah produk berupa nilai-nilai dan keyakinan masyarakat tentang perempuan dan pernikahan misalnya istilah perawan tua, usia ideal menikah dan sebagainya.
Ternyata tidak cukup terpagari saja, bahkan perempuan juga harus bisa menghadapi kenyataan pahit lainnya, yakni kedekatan dan kemiripan ”nasib”-nya dengan barang dagangan. Jika barang terbatasi oleh masa berlaku dan bergunanya agar dapat dikonsumsi atau digunakan dengan kualitas yang baik, maka sepertinya hal itu pun terjadi pada perempuan. Perempuan seperti dianggap punya masa kadaluwarsa untuk menikah. Jika bagi barang, masa kadaluwarsa itu berarti menurun kualitas bahkan tidak dapat dikonsumsi sama sekali, maka bagi perempuan hal itu dikaitkan dengan menurunnya kemampuan reproduksi perempuan terkait dengan usia. Karena secara biologis perempuan dianggap terbatasi waktu dalam hal kemampuan reproduksinya. Artinya makin tua usianya, makin mendekati waktu “kadaluwarsa” sehingga memperkecil kesempatan mendapat jodoh. Itulah nalar yang berkembang di masyarakat.
Tidak heran jika akhirnya yang terjadi adalah perlombaan atau persaingan, yang semoga memang sehat, untuk menjual suatu produk yang dibayang-bayangi masa kadaluwarsa. Karena bagaimana pun dalam suatu perdagangan hanya ada keuntungan yang dicari dan kerugian yang dihindari. Muncullah pendapat yang kemudian diyakini banyak orang tentang batas usia pernikahan yang ideal bagi perempuan, yakni antara 25 dan 30 tahun. Jika ditilik maka alasannya tidak lepas dari kekhawatiran terhadap masa produktif fungsi reproduksi perempuan sekaligus mempertimbangkan kedewasaan psikologis perempuan yang mungkin telah berkembang di usia itu.
Akan muncul beberapa kemungkinan terkait hal tersebut, misalnya perempuan akan berlomba-lomba mencari jodohnya, baik dengan sungguh-sungguh dan hati-hati ataukah seadanya saja. Beruntunglah mereka yang berhasil menemukan jodohnya yang sesuai dan tepat pada waktunya. Nah, “cukup beruntung” bagi mereka yang menemukan jodoh seadanya dan berhasil menikah di batas usia ideal pernikahan tersebut. Maka bagi mereka yang bukan golongan keduanya, yakni perempuan yang sampai di atas usia 25 atau 30 tahun belum menikah dianggap merugi. Dan mereka harus bersiap dengan segala konsekuensinya.
Para perempuan yang (dianggap) kurang beruntung itu terpaksa menerima label yang jadi momok menakutkan yaitu “perawan tua”. Suatu ungkapan yang tidak cuma bisa membuat kuping memerah, tapi juga sakit hati. Karena bagaimana pun itu berdampak besar dan luas baik bagi si perempuan sendiri hingga keluarganya yang juga harus kecipratan “penghakiman” masyarakat ini. Ini sangat memberatkan perempuan secara batin dan bayangkan bagaimana kondisi psikologis mereka, karena mereka juga sebenar-benarnya adalah manusia. Tidak heran jika perbuatan yang demikian, yang dikira itu “biasa” itu dapat mengantarkan si perempuan yang kebetulan “tidak sanggup” dengan tekanan tersebut pada berbagai gangguan kejiwaan termasuk depresi. Bukan tidak mungkin hal itu justru mengundang keputusasaan hingga kenekatan melakukan tindakan lainnya.
Lain lagi jika si perempuan tangguh dan tak peduli, maka yang akan terjadi pengabaian. Tetapi kalau mau jujur, seberapa banyak perempuan yang tetap tangguh jika terus-menerus menerima tekanan yang demikian di masyarakat? Berapa banyak perempuan yang dalam kondisi masyarakat saat ini, yang berani punya sikap berbeda soal pernikahan, waktu menikah misalnya, terlebih jika ia minoritas?
Masyarakat memang berfungsi dalam hal kontrol sosial, tidak ada yang salah memang dan justru itu yang seharusnya dilakukan. Masalahnya, apakah masyarakat saat ini sudah bijak? Sudahkah mereka memahami apa-apa yang yang bisa dikontrolnya dan yang tidak? Apakah bijak jika masyarakat berwenang untuk melekatkan label “perawan tua” bagi perempuan. Padahal, sejatinya itu merupakan keputusan pribadi perempuan sebagai seorang individu yang kebetulan anggota masyarakat. Wajar sekali bila tiap individu layaknya perempuan memiliki keinginan, keyakinan dan keputusan sendiri-sendiri dan tidaklah seragam. Tidak bijak, jika karena semua itu kemudian masyarakat baik dengan sengaja atau tidak, menganggap, memperlakukan perempuan layaknya barang dagangan.
Mulai sekarang, berhentilah mengolok-olok, mengejek, mengintimidasi, menggunjingkan bahkan menyebut perempuan dengan istilah perawan tua atau tidak laku. Karena, perempuan adalah seorang makhluk yang dunianya adalah kehidupan, dan jangan samakan dengan barang dagangan yang dunianya hanya seputar jual-beli dan untung-rugi.
Maya Atri adalah seorang perempuan yang pernah belajar sosiologi, pejuang penggapai mimpi dan percaya pada intuisi. Punya hobi mendengarkan, terutama musik dan radio. Suka pergi ke perpustakaan untuk baca, cari buku dan kadang cuma nongkrong.